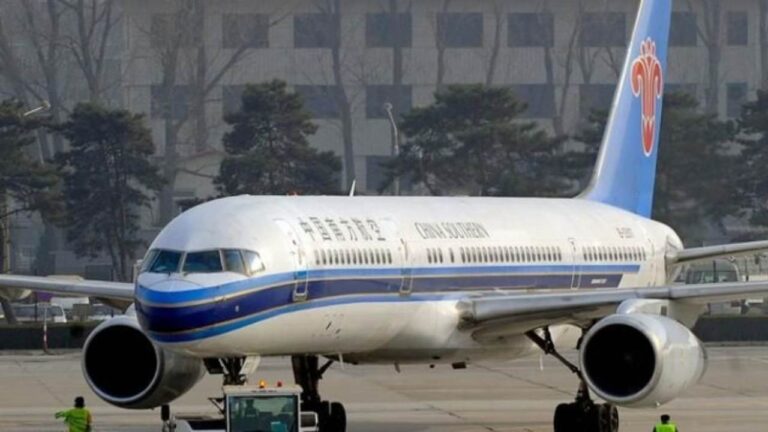Demokrasi Indonesia dan Krisis Fiskal yang Kian Terbuka
Foomer Official – Lebih dari sepekan setelah insiden penjarahan rumah Sri Mulyani, Presiden Prabowo Subianto akhirnya melakukan reshuffle kabinet. Pergantian posisi Menteri Keuangan menjadi sorotan publik, terlebih karena peristiwa politik ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya keresahan ekonomi. Gambar dan video yang tersebar di media sosial menggambarkan bagaimana massa aksi menjarah rumah Sri Mulyani, Ahmad Sahroni, dan sejumlah anggota DPR. Peristiwa tersebut bukan sekadar drama politik, melainkan cermin rapuhnya kondisi fiskal dan meningkatnya ketidakselarasan sosial di Indonesia.
Kesenjangan Sosial Sebagai Pemicu Kemarahan Publik
Gelombang demonstrasi yang awalnya dipicu isu tunjangan DPR ternyata memiliki substansi lebih dalam. Poverty Factsheet Bank Dunia (Juni 2025) mencatat bahwa lebih dari dua pertiga penduduk Indonesia, yakni sekitar 194 juta orang, hidup dengan pengeluaran kurang dari Rp50.400 per hari. Ditambah lagi, lebih dari separuh tenaga kerja masih berada di sektor informal tanpa perlindungan sosial. Ketidakadilan ini membuat generasi muda sulit naik kelas secara ekonomi, sehingga memperbesar rasa frustrasi dan mendorong aksi massa.
Baca Juga : Misteri Sanatorium Terbengkalai di Pegunungan Atlas Maroko
Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Inklusif
Meski pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5–5,5 persen, kenyataannya pendapatan riil masyarakat tidak mengalami peningkatan berarti. Alih-alih menyejahterakan rakyat, pertumbuhan ini justru memperlebar jurang ketimpangan. Generasi muda yang seharusnya menjadi motor pertumbuhan ekonomi terjebak dalam pengangguran dan pekerjaan berupah rendah. Kontradiksi ini menjelaskan mengapa aksi massa berkembang cepat menjadi kritik atas rapuhnya fondasi fiskal Indonesia.
Menggunakan Kerangka IMF untuk Menilai Risiko
Jika memakai kerangka IMF (A Framework For Assessing Fiscal Vulnerability), situasi Indonesia kini menunjukkan tanda-tanda kerentanan serius. Pertama, posisi awal fiskal sudah berada dalam jebakan utang. Pemerintah berencana menarik utang baru senilai US$48,4 miliar pada 2026, namun 77 persen hanya untuk membayar bunga utang lama. Kedua, pasar menunjukkan sensitivitas tinggi, terbukti dari anjloknya IHSG 2,27 persen dan rupiah melemah hampir 1 persen pasca demonstrasi. Ketiga, dari sisi keberlanjutan jangka panjang, rasio pajak yang jatuh ke 8,42 persen memperlihatkan basis penerimaan yang lemah.
Lemahnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Fiskal
Selain masalah angka, kelemahan struktural menjadi faktor paling mengkhawatirkan. Korupsi dan lemahnya akuntabilitas membuat belanja negara tidak diarahkan ke sektor prioritas. Gelombang demonstrasi justru mengungkap bahwa persoalan fiskal bukan sekadar ekonomi, melainkan krisis politik yang lebih dalam. Kombinasi utang baru untuk membayar utang lama, rendahnya penerimaan pajak, dan lemahnya disiplin anggaran menciptakan textbook case kerentanan fiskal yang tidak bisa diabaikan.
Indonesia di Titik Persimpangan Sejarah
Meski ruang manuver fiskal semakin sempit, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki arah kebijakan. Demonstrasi dan reshuffle kabinet bisa menjadi momentum koreksi demokrasi yang sehat. Aksi massa bukan hanya bentuk kemarahan publik, tetapi juga dorongan untuk reformasi menyeluruh. Jika diarahkan dengan benar, gejolak politik ini bisa memperkuat institusi, menegakkan akuntabilitas fiskal, serta memfokuskan belanja negara pada sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
Mengingat Pelajaran dari Krisis 1998
Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah berada di titik krisis yang sama pada 1998. Saat itu, gejolak ekonomi justru membuka jalan reformasi politik yang membentuk fondasi baru bagi demokrasi. Kini, peluang serupa terbuka kembali. Pertanyaannya, apakah para pengambil kebijakan mampu memanfaatkan momentum ini untuk menyelesaikan proyek reformasi ekonomi yang belum tuntas? Jika iya, maka krisis hari ini bisa menjadi batu loncatan menuju Indonesia yang lebih adil dan berkelanjutan.